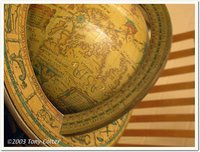The same as grandmaster of Silat Seni Gayong, Dato' Meor Abdul Rahman, grandmaster of Silat Sendeng, Long Mamat also the descendants Bugis. Originally from Sulawesi, the wanderlust of the Bugis ensured that they were well-travelled throughout Nusantara and beyond, bringing with them their knowledge, their culture, and their combat arts. In Malaysia, among the more popular and recognizable of these is Seni Silat Sendeng.
Silat
Sendeng founded by Allahyarham Long Mamat and expanded by Allahyarham
Haji Hamid bin Haji Hamzah, named this silat by Seni Silat Sendeng Muar.
First center under Allahyarham Haji Hamid is born at Sungai Mati, Muar,
Johor Darul Takzim. After Allahyarham Haji Hamid past away on 19 May
1990, his younger brother, Allahyarham Haji Ismail bin Haji Hamzah was
choosen to lead Seni Silat Sendeng and replaced as ‘Guru Utama’
(Grandmaster). On 11 July 1992, Seni Silat Sendeng Muar was register by
the name ‘Pertubuhan Seni Silat Sendeng Malaysia’ with combining 7
branch of country like Johor, Melaka, Pahang, Perak, Kuala Lumpur,
Selangor and Negeri Sembilan. Now, Pertubuhan Seni Silat Sendeng