Oleh MERAN ABU BAKAR
Gambar RASHID MAHFOF
 |
Ugik M sedia membantu ahlinya termasuk dalam bidang perniagaan.
|
DENGAN hasrat untuk menyatupadukan masyarakat Bugis di seluruh Malaysia, Persatuan Kebajikan Ekonomi Bugis Malaysia (Ugik M) telah ditubuhkan sejak setahun lalu di Johor Bahru, Johor.
Presidennya, Lokman Junit berkata, objektif penubuhan persatuan itu bagi mengukuhkan ekonomi masyarakat Bugis yang kebanyakannya melakukan kerja-kerja berkebun dan berniaga.
Dengan adanya persatuan itu juga ujarnya, satu rangkaian perniagaan boleh dijalankan di kalangan masyarakat Bugis termasuk bagi mendapatkan produk niaga daripada kampung asal mereka di Sulawesi Selatan.
Antara produk yang boleh diperoleh daripada Sulawesi Selatan adalah seperti sutera Bugis yang halus dan lembut, selendang, songkok Bugis, buku, pakaian dan produk makanan.
Beliau yang juga pemilik Ugik Technologies di Pekan Francis Pulai, Skudai, Johor berkata, syarikatnya ada menjual segala barangan dan keperluan yang diperlukan oleh masyarakat Bugis. Dengan kata lain, Ugik Technologies adalah merupakan pusat pemborong produk Bugis.
Menurut Lokman, pada masa kini Ugik M mempunyai slebih 1,000 orang ahli di seluruh Malaysia. Selain Johor, masyarakat Bugis juga tinggal di Selangor, Melaka, Perak, Pahang dan Sabah.
''Paling ramai ialah di Pontian, Johor dan mereka aktif berniaga atau berkebun yang menjadi sumber pendapatan mereka,'' katanya kepada Mega baru-baru ini.
Lokman menambah, bagi mengenalkan asal-usul masyarakat Bugis di negara ini yang berasal dari Sulawesi Selatan, beliau merancang untuk membuat projek pertama melancong ke Sulawesi pada musim cuti sekolah bulan Jun ini.
Program lawatan selama tujuh hari enam malam ini mengenakan tambang sebanyak RM2,000 seorang termasuk tambang, penginapan, perjalanan serta lawatan semasa di sana dan makan minum.
Di antara aktiviti yang akan diadakan semasa berada di Sulawesi ialah melawat pusat pemborong Sulawesi, melawat kilang, melawat Muzium Lagaligo yang menjadi kubu pertahanan daripada serangan Belanda dan sebagainya.
''Bagi mereka yang masih mempunyai saudara-mara, mereka boleh pulang ke kampung halaman dan menziarahi sanak saudara yang masing tinggal di sana,'' tambah Lokman.
Kepada yang berminat, bolehlah menghubungi Lokman di 016-7975810.end_of_the_skype_highlighting







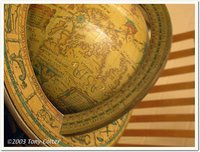
 Orang bugis memiliki berbagai ciri yang sangat menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat di wilayah nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India. Dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka.
Orang bugis memiliki berbagai ciri yang sangat menarik. Mereka adalah contoh yang jarang terdapat di wilayah nusantara. Mereka mampu mendirikan kerajaan-kerajaan yang sama sekali tidak mengandung pengaruh India. Dan tanpa mendirikan kota sebagai pusat aktivitas mereka. Selanjutnya sejak abad ke 17 Masehi, Setelah menganut agama islam Orang bugis bersama orang aceh dan minang kabau dari Sumatra, Orang melayu di Sumatra, Dayak di Kalimantan, Orang Sunda dijawa Barat, Madura di jawa timur dicap sebagai Orang nusantara yang paling kuat identitas Keislamannya.
Selanjutnya sejak abad ke 17 Masehi, Setelah menganut agama islam Orang bugis bersama orang aceh dan minang kabau dari Sumatra, Orang melayu di Sumatra, Dayak di Kalimantan, Orang Sunda dijawa Barat, Madura di jawa timur dicap sebagai Orang nusantara yang paling kuat identitas Keislamannya.




